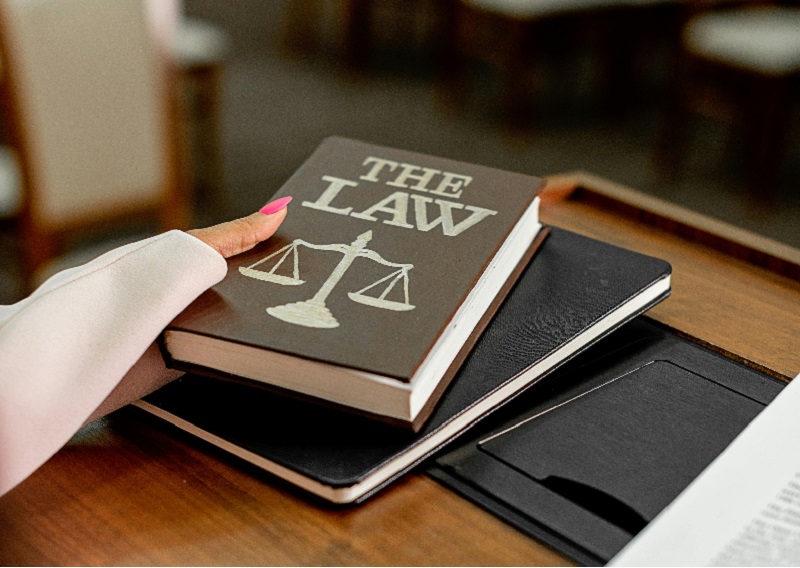BacaHukumm.com – Putusan bersalah terhadap Thomas Trikasih Lembong oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyisakan tanda tanya serius terhadap arah dan orientasi penegakan hukum di Indonesia. Dalam perkara yang berkaitan dengan kebijakan impor gula saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag), Tom dijatuhi pidana penjara meskipun tidak terbukti menerima suap (gratifikasi), tidak memperkaya diri sendiri maupun orang lain, dan tidak memiliki kepentingan pribadi (personal interest) dalam pengambilan keputusan tersebut.
Pertanyaannya sederhana namun fundamental, yaitu bagaimana mungkin seorang pejabat publik yang menjalankan fungsi diskresi administratif sebagai bagian dari kebijakan strategis nasional justru diposisikan sebagai pelaku tindak pidana korupsi, sementara aktor intelektual (intellectual dader) maupun pembuat keputusan utama (policy maker) tetap berada di luar jangkauan proses hukum?
Dalam logika hukum yang adil dan proporsional, seharusnya terdapat pembedaan tegas antara perbuatan maladministrasi dengan delik pidana. Namun dalam kasus ini, asas legalitas (nullum crimen sine lege) seperti dibiaskan oleh tafsir sempit terhadap Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, yang menuntut adanya kerugian keuangan negara. Padahal, baik mens rea (niat jahat) maupun actus reus (perbuatan melawan hukum) dalam diri Tom tidak pernah teridentifikasi secara eksplisit. Ia hanya menjalankan kebijakan yang secara politik didesain dalam forum eksekutif, dan bahkan menurut pengakuannya, merupakan instruksi lisan dari Presiden sebagai superior chain of command.
Sayangnya, pernyataan tersebut tidak dianggap cukup oleh pengadilan karena tidak didukung alat bukti tertulis. Di sinilah problem sistemik pembuktian dalam hukum acara pidana menjadi terang, bahwa birokrasi pemerintahan modern tidak selalu bekerja dalam relasi hukum tertulis, melainkan kerap menggunakan jalur-jalur informal dan discretionary power. Jika seluruh kebijakan yang tidak terdokumentasi secara formil lantas ditarik menjadi objek pidana, maka hal ini membuka ruang kriminalisasi kebijakan publik (criminalization of policy), sebuah praktik yang membahayakan prinsip due process of law dan dapat membunuh keberanian para pembuat kebijakan di masa depan.
Lebih dalam, patut dipertanyakan mengapa hanya Tom yang dijerat, padahal keputusan tentang relaksasi impor gula tidak dilakukan secara unilateral. Prinsip pertanggungjawaban kolektif (collegial responsibility) dalam sistem administrasi pemerintahan diabaikan. Tom dijadikan satu-satunya pihak yang menanggung risiko hukum, sementara asas equality before the law tampak lumpuh di hadapan relasi kekuasaan. Ini bukan sekadar bentuk ketidakadilan yuridis, melainkan distorsi struktural terhadap asas ultimum remedium, di mana hukum pidana seharusnya menjadi jalan terakhir, bukan alat politik untuk menjatuhkan.
Terlebih lagi, pemidanaan ini terjadi dalam konteks politik pasca pemilu, di mana konstelasi kekuasaan tengah disusun ulang. Tom Lembong dikenal sebagai teknokrat yang kerap memiliki pandangan berbeda dari poros kekuasaan dominan. Maka tidak berlebihan jika terdapat indikasi instrumentalitas hukum (law as a political instrument), yakni penggunaan hukum untuk membungkam atau mengasingkan figur-figur yang dianggap “berseberangan”.
Pesan yang terbaca dari putusan ini sangat mengkhawatirkan, bahwa dalam sistem hukum yang dikungkung kepentingan politik, integritas dan profesionalitas pejabat publik tidak menjadi jaminan perlindungan hukum. Ketika pelanggaran hukum oleh aktor besar kerap dibungkus “diskresi”, sementara kebijakan progresif justru dikriminalisasi, maka masyarakat berhak bertanya “Apakah hukum masih menjadi pelayan keadilan, atau telah menjadi pelayan kekuasaan?”
Putusan terhadap Tom Lembong bukan hanya preseden buruk bagi masa depan tata kelola pemerintahan, tetapi juga peringatan keras bagi generasi baru birokrat dan pemimpin publik. Jika tidak ada reformulasi dalam paradigma penegakan hukum kita, maka keberanian untuk bertindak dalam kepentingan bangsa akan mati sebelum lahir dan terbunuh oleh ketakutan akan delik yang dimanipulasi.
Penulis:
Adjie Pramana Sukma, S.H.
Aktivis Hukum dan HAM